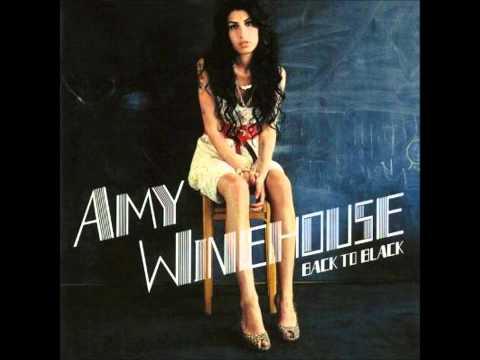Halo!
Kangen nggak sama aku?
*ditabok.
Well, here i am, datang bawa cerita baru yg bener-bener berbeda karena mengusung "crime fiction"
Nggak romance?
Romance-nya tetep kuat di dalamnya dong. Jadi bagi kamu penggemar romance, tetep bisa menikmatinya.
So enjoy it!
oOo
Adu mulut di ruang tamu terdengar sampai kamarku. Aku mengusap mata, menggusah kantuk yang tersisa. Pipiku kaku karena menempel di atas buku cukup lama—ternyata aku tertidur selagi mengerjakan PR.
Teriakan-teriakan dari ruang tamu semakin keras. Aku duduk lebih tegak, menajamkan pendengaran. Ada suara Ayah dan beberapa suara orang dewasa lain.
Kemudian, mendadak hening.
Napasku tertahan. Perasaanku tidak nyaman.
Samar, aku mendengar Ayah berkata, "Turunkan senjata kalian!"
Aku bisa membayangkan adegan di luar sekarang. Ada yang menodongkan senjata kepada Ayah. Situasinya tibatiba menjadi berbahaya. Kurasa, aku tidak bisa terus berdiam saja.
Aku beringsut ke sisi tempat tidur dan menarik laci di bawah dipan. Glock milikku tersimpan di sana. Terakhir kali berlatih me nembak, aku ingat masih menyisakan beberapa butir peluru di ma gasinnya. Aku mengambil benda itu dengan hatihati agar tidak menimbulkan suara, lalu berjinjit ke pintu.
"Aman, Fredy, kami sudah pasang peredam."
"Lo mau pasang peredam dulu?"
Terdengar tawa mengejek. "Beneran mau melawan? Kami bertiga, Fredy. Nyerah ajalah. Pilih jalan damai dan turuti mau kami."
Mataku membulat. Itu jelas sebuah ancaman.
Aku menarik pintu kamar. Mataku langsung menangkap keberadaan tiga pria lain, dua orang di antaranya tengah menodongkan senjata kepada ayahku. Pria yang paling dekat dari posisiku memegang senjata yang sama dengan milikku, Glock. Dia menoleh perlahan—mungkin suara derit pintu sampai ke telinganya. Kemudian, dua temannya yang lain ikut menoleh. Satu yang tirus menyeringai, sementara yang berdiri di dekat pintu keluar memucat. Ayahkulah yang terakhir menoleh dengan gerakan perlahan sekaku robot. Matanya melebar nanar ketika memandangku. Kepalanya seperti berusaha menggeleng, melemparkan isyarat tanpa suara.
"Punya bantuan, Fredy?" tanya pria tirus.
"Gu-gue dengar Valerie jago nembak," si pria pucat terbata. Dia takut kepadaku? Anak 13 tahun ini? Kenapa?
"Kalian sedang apa?" tanyaku waspada.
"Mau ikut main?" tanya si pemegang Glock sambil menelengkan kepala.
Aku bergantian mengamati Ayah dan ketiga pria yang masih saling todong meski mata mereka tertuju kepadaku. Aku menguak pintu lebih lebar. Tiga pasang mata milik para pria yang tidak kukenal itu itu membelalak ketika melihat benda di tanganku.
"VALERIE, LA—"
Kalimat ayahku tidak terselesaikan karena si pemegang Glock memutar kepala ke arah Ayah. Sedetik, aku merasa panik, memiliki firasat mengenai apa yang akan terjadi. Instingku mengambil alih dan tanganku bergerak lebih cepat daripada otak. Aku menembak.
Telingaku berdenging mendengar rentetan tembakan yang sahut menyahut. Apakah kedua pria bersenjata itu membalas? Apakah ayahku ikut menembak? Aku tidak bisa mencerna sekelilingku. Hanya telunjukku saja yang terus menekan pelatuk hingga macet, hingga tidak ada lagi peluru yang bisa dimuntahkan pistol itu. Napasku memburu. Dadaku naik turun. Telapak tanganku terasa panas dan lenganku sakit menahan efek sentakan senjata yang berulang. Aku menyisir ruangan dengan pandangan yang mendadak kabur. Aku menggoyangkan kepala untuk menjernikan pikiran.
Saat itulah aku mendengar suara gemeresik dan melirik, mendapati si pria berwajah pucat beringsut mundur ke arah pintu. Sepertinya dia tidak terluka. Peruntungannya bagus juga. Terutama karena sekarang aku kehabisan peluru dan tidak bisa menyerang.
"A-aku akan pergi. Oke?" cicitnya sambil mengangkat tangan tanda menyerah.
Pria itu dengan tergesa membuka pintu dan kabur tanpa menutupnya kembali. Saat itulah aku melihat kehadiran sosok lain di sana, dari celah pintu yang terbuka. Nenek Maida, tetanggaku, menatap dengan mata terbelalak. Bibirnya terbuka dan jeritan keras nyaris terdengar jika dia tidak buru-buru membekap mulutnya sen diri. Aku menunduk ke arah Glock di tanganku yang tidak dipasangi peredam.
"Nek, aku—" Suaraku lebih parau daripada yang kuduga. Tenggorokanku kering, membuatku kesulitan berkata-kata. Aku dirundung bingung dan kehilangan daya.
Nenek Maida terhuyung pergi dan aku tidak peduli. Mataku terpaku pada tiga tubuh yang tergeletak di ruang tamu. Si pria pemegang Glock, si pria tirus, dan terakhir ....
Seluruh fokusku tertuju kepada sosok itu. Sosok yang separuh tubuhnya ambruk ke sofa, sementara sisanya di lantai. SIG Sauer terlepas dari jarinya yang menjuntai.
Betapa ingin aku memanggilnya supaya dia bisa menenangkanku, tetapi takut dia tidak menjawab.
Betapa ingin aku mengguncang tubuhnya, tetapi takut dia tetap tidak bergerak.
"A-Ayah?"
Hanya satu kata itu yang bisa kupaksakan keluar dari mulutku yang kering. Sisanya, aku memanggilnya puluhan kali, dalam hati.
Namun, ayahku tidak pernah bangun lagi.[]

KAMU SEDANG MEMBACA
Alegori Valerie
Mystery / ThrillerValerie ingin cepat mati. Hidupnya kehilangan arti. Setelah ibunya bunuh diri, Valerie dituduh membunuh 3 orang, termasuk ayah kandungnya sendiri. Hingga Valerie bertemu Haezel, mahasiswa hukum yang berkeras memfilmkan kisah hidupnya demi menuntut...