***
"Apa itu sakit?" Tanyaku sambil menengok ke arah bekas lukanya. Marsel terlalu sering jatuh di arena. Seharusnya di usianya yang masih remaja itu, dia bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk hal-hal yang lebih baik. Sekolah dengan baik, makan dengan baik, bahagia dengan baik, dan jatuh cinta dengan baik. Ya, remaja tak bisa untuk tak jatuh cinta.
"Pada awalnya, ya. Sekarang sudah tidak." Dia menutup lagi lututnya dengan celana jeans sobek-sobek yang justru bolong di tengah-tengah lutut itu. Dasar anak nakal.
"Kau tahu? Luka itu unik. Bekasnya masih bisa memudar oleh waktu. Hal yang membuatnya awet adalah rasa sakitnya."
"Dari mana Ibu mendapatkan kata-kata itu?"
"Kau kira Ibu mencomotnya dari jalan, hah?"
"Tidak. Maksudku, itu benar. Semua jatuh pasti menimbulkan luka."
"Termasuk jatuh hati?" Tanyaku sambil tersenyum menatapnya. Sekaligus menyindirnya karena baru saja mengakhiri hubungan dengan kekasihnya. Sama sepertiku.
"Ya. Termasuk jatuh hati. Itu pun menimbulkan luka. Di hati." Dia menjawab dengan tatapan kosong ke arah ujung sepatunya. Aku tahu arti tatapan itu. Dia pasti teringat dengan mendiang kekasihnya. Oh, Tuhan. Mengapa remaja laki-laki di sampingku ini begitu banyak menyimpan rahasia hati yang membuatku harus menerka-nerka? Sial sekali.
Aku terdiam. Tak membalas kalimat terakhirnya. Sama sepertinya, benakku hanyut dibawa kenangan. Mengalirkan segala ingatan pada Langit. Setelah bersusah payah kembali ke kota perantauan dengan menggunakan bus kota, akhirnya aku tiba di alamat yang Marsel kirimkan padaku. Meninggalkan Langit di tempat penuh cerita antara aku dengannya.
Aku menengadah. Langit di atas sana perlahan gelap. Bukan. Bukan karena hari sudah petang, justru kukira mendung ini pertanda bahwa akan terjadi hujan. Entahlah. Dalam setiap keadaan yang terjadi dalam hatiku, langit selalu sepakat bersemburat. Seolah dia tahu, begitulah keadaan Langit saat itu. Aku menelan ludah. Enggan melanjutkan pembicaraan sementara Marsel masih menendang-nendangkan kakinya ke udara.
"Hentikan. Lukamu itu baru. Jangan kau gerakkan terus kakimu. Syukur hanya luka ringan, kalau darahnya banyak nanti kau akan pingsan. Siapa yang akan membantumu?" Aku geram. Setelah Marsel menceritakan kejadian sebenarnya, aku bergegas menemuinya hingga mengorbankan Langit. Dia jatuh (lagi) di arena. Sudah kubilang, jiwanya tidak pernah berada di tempat lain selain yang dia sebutkan itu. Kelab, arena, atau puncak.
"Tentu saja Ibu. Siapa lagi? Bu, jangan terlalu mencemaskan luka orang lain. Pedulikan saja dulu luka sendiri. Ibu terlalu mengabaikan itu. Bukankah setiap jenis luka rasanya sama, Bu? Sakit."
Pertanyaan Marsel membuat lidahku kelu. Aku tak berkutik sedikitpun bahkan napasku tertahan. Jauh di luar dugaanku, dia selalu bersikap berbeda dari siswaku yang lainnya. Caranya memperlakukanku sebagai seorang guru, mungkin memang jauh dari kata sempurna. Namun, menurutku, itulah caranya sendiri bersikap yang seharusnya padaku. Dengan gayanya itu, aku tahu betul, dia menghormatiku bahkan memedulikanku.
Anak ini masih menatapku. Seolah menuntut jawaban dariku atas pertanyaannya. Benar-benar pandai. Dia selalu diam di kelas, tak mengajukan pertanyaan terkait materi pembelajaran. Namun, dia yang paling aktif mengajukan pertanyaan berkenaan dengan kehidupanku. Sial. Pertanyaan ini sulit kujawab.
"Apa kau tidak memiliki pertanyaan lain? Mengapa tidak kau tanyakan saja mengenai mata pelajaran yang Ibu ajarkan? Atau tidak kau jelaskan mengapa kau menghilang selama satu minggu?"
"Kalau aku bertanya pelajaran, aku tahu Ibu sudah tahu jawabannya. Ibu orang cerdas, bukan? Maka dari itu, aku bertanya sebuah pertanyaan yang sulit ditemukan jawabannya. Dan, aku hanya ingin menghabiskan waktuku di arena. Di rumahku terasa rumit."
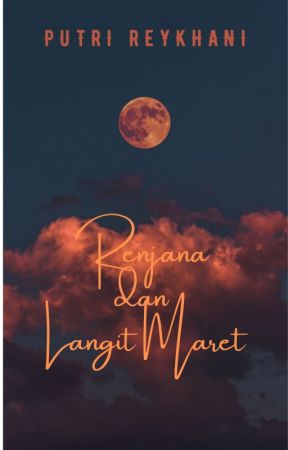
KAMU SEDANG MEMBACA
Renjana dan Langit Maret
General FictionRenjana, seorang guru muda yang dihadapkan dengan persoalan pelik terkait profesinya. Rasa bersalah yang terus menghantuinya setiap hari membuat malam-malamnya terasa lebih panjang. Setelah berupaya keras menyembuhkan masa lalunya, takdir membawanya...
