Mention: self harm, self attack, mental issues
***
Lavender. Satu nama itu, kukenal selama dua tahun terakhir. Aku tidak tahu nama lengkapnya, di mana dia tinggal, seperti apa wajahnya, bahkan aku juga tidak tahu dia perempuan atau laki-laki. Aku mengenalnya pertama kali di sebuah grup Facebook, berisi orang-orang introvert. Di dalam grup itu aku jarang berinteraksi, tapi sebuah akun dengan nama Lavender tiba-tiba mengajakku mengobrol melalui inbox pribadi.
Awalnya kami hanya mengobrol biasa, dengan dia yang banyak bertanya dan aku menjawab. Dari obrolan kami, aku merasa bahwa Lavender adalah orang yang ceria dan mudah bergaul. Hal yang sempat membuatku heran, kenapa dia bergabung di dalam grup introvert itu. Tapi keheranan itu tak lagi penting setelah kami bisa lebih akrab.
Sekitar enam bulan kenal, aku kembali dibuat heran oleh Lavender. Tiba-tiba saja, dia menebak bahwa hidupku tidak baik-baik saja. Dia bilang, aku merasa tertekan. Saat aku bertanya bagaimana dia bisa berpikir seperti itu, dia hanya mengatakan insting seorang teman, dari obrolan kami selama ini.
Jujur, awalnya aku takut. Dia hanya seorang gadis (atau laki-laki?) yang kukenal dari sosial media. Tentu saja aku merasa was-was ketika dia menyinggung masalah pribadi. Tapi lagi-lagi dia menenangkan dengan menuliskan pesan bahwa dia tidak mau tahu atau mencampuri urusanku. Dia bilang, dia juga punya masalah hidup yang membuatnya tertekan. Lalu ingin berbagi kepadaku cara untuk menenangkan diri sendiri saat rasa tertekan itu muncul.
Dan sampai sekarang, kami masih berteman. Bedanya, ruang obrolan kami berganti. Bukan lagi Facebook, tapi direct message Instagram. Walaupun komunikasi kami juga tidak seintens dulu. Paling-paling dua atau tiga minggu sekali, itu pun jika tidak sibuk. Dan selama itu pula, kami tak saling tahu wajah masing-masing. Karena entah bagaimana ceritanya, kami juga sama-sama tidak suka mem-posting wajah di sosial media.
Wounds never betray. Feel the pain. See the blood. Get a scar. Itu yang dia kirimkan tadi. Dalam setiap pesan singkatnya, Lavender hampir selalu menuliskan itu. Seperti mantra pengingat, bahwa aku masih bisa tersenyum dalam kubangan luka. Bahwa rasa sakit bisa kunikmati dengan bahagia. Dan sekarang, aku tidak sabar melakukan itu.
"Tomi udah pulang, Li."
Ucapan Doni yang duduk di kursi kemudi, membuyarkan lamunanku. Mataku membulat. Benar saja, di halaman rumah, mobil Yonggi terparkir. Seketika kepanikan melandaku. Ini memang sudah malam. Kami baru pulang karena tadi Doni mengajak makan, lalu mengantar Rena dan Zia dulu ke panti asuhan.
"Lo takut?"
Aku meringis, berusaha untuk tidak gemetar saat melepaskan sabuk pengaman. "Tadi kan aku nggak izin."
"Salah gue." Doni mengusap dahinya. "Ya udah gue temenin masuk, yuk. Lagian Nenek kan dijemput Mama tadi buat nginep di rumah gue."
"Tapi nanti Yonggi marah sama kamu."
"Nggak masalah. Asal jangan ke elo." Doni melepas sabuk pengaman, kemudian membuka pintu. "Yuk."
Mengembuskan napas berat, aku ikut turun. Kami berjalan beriringan menuju beranda rumah. Aku dengan ketegangan yang nyata, sementara Doni kelihatan santai. Dia bahkan masih sempat melempar cengiran dan memintaku untuk tenang. Tapi tentu tidak bisa. Entah kenapa, aku berfirasat bahwa Yonggi akan marah besar.
Dan sepertinya itu bukan sekadar firasat. Karena setelah membuka pintu depan, Yonggi berdiri di sana. Dengan mata menyorot tajam dan penuh emosi. Rahangnya mengetat. Aku bahkan langsung menunduk karena takut.
"Sorry, Tom, tadi gue ajak Lili makan dulu jadi pulangnya agak malem." Itu ucapan Doni, yang langsung dibalas sinis oleh Yonggi.
"Pulang lo."
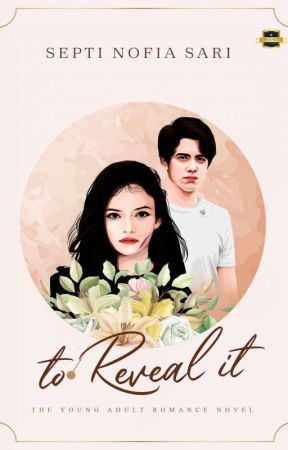
KAMU SEDANG MEMBACA
To Reveal It (REPOST)
Ficción GeneralHaiiiii yang baru buka cerita ini, selamat datang. Sebenarnya cerita ini sudah terbit, ready versi PDF juga. Tapi aku pengen repost biar yang belum sempat baca PDF atau buku, bisa baca gratis di sini. Jangan lupa vote dan komen, ya. Happy reading ♡ ...
