Selepas maghrib, jenazah abah sudah dimandikan, sudah disholatkan. Seluruh keluarga berkumpul, membaca surat yasin, membaca tahlil, mengirim doa.
"Mas, njenengan siose sing ngijabne Alia, to?" Gus Ulin bertanya dengan mata sembab.
Gus Zaka mengangguk pelan. Sesuai kesepakatan, pernikahan ini harus disegerakan, meski di depan jenazah abah. Supaya abah masih bisa mendampingi putrinya, untuk terahir kali.
Kang-kang mempersiapkan meja akad di depan jenazah abah. Seadanya, tanpa bunga-bunga, tanpa ornamen pernikahan yang layak. Dekor pernikahan yang mewah sudah tidak digubris. Hiasan bunga trisan yang disusun berjejer di panggung dekor seolah telah layu, tidak mekar lagi. Pernikahan ini dilangsungkan di masjid pondok, tempat jenazah abah dishalatkan.
Kami semua tidak ada yang berganti baju. Aku masih mengenakan kemeja cokelat yang kini telah lusuh. Ning Alia mengenakan gamis brokat yang sejak tadi ia pakai. Wajahnya pucat, tidak dipoles make up sama sekali. Mbak Ratih terus memeluknya, memberi kekuatan. Mbak Asna dan Mbak Zulfa duduk di belakang, mulutnya terus berdzikir.
Seluruh keluarga berkumpul, seluruh santri berkumpul.
"Sampean sing ikhlas yo, Kang," ucap Gus Adnan sambil menepuk pundakku.
"Pangestunipun, Gus."
"Sampean kudu sabar momong Alia. Ojo digetak, ojo digalaki, arek e kawit cilik ora tau dikasari."
Aku mengangguk kecil. "Insyaallah, Gus."
"Pancen kersane Gusti Allah iku gak ono sing reti yo, Kang. Tibake omonganku mau awan kok kedaden. Aku pengen sampean cepet ndue pendamping. Ora ono sing ngiro, jebule.." Gus Zaka tidak meneruskan kalimatnya, namun kami sudah paham.
Memang tidak ada yang mengira, rupanya takdir membawaku ke jalan yang seperti ini. Dalam impianku, pernikahanku kelak akan dilaksanakan dengan meriah meski sederhana. Tidak harus mewah, tapi semua yang hadir bisa turut merasai kebahagiaan kami. Kami akan saling melempar senyum di pelaminan, seolah berkata kepada semua orang bahwa kami adalah pasangan paling bahagia hari itu. Namun takdir Allah selalu tidak bisa ditolak. Skenario-Nya berkata lain.
Aku duduk berhadapan dengan Gus Zaka. Di sampingku, Ning Alia terduduk lesu. Kepalanya terus menunduk. Bu Nyai Khodijah duduk di sebelah kanannya, mengusap pundak keponakan yang sudah seperti puterinya sendiri.
"Awakmu sing ikhlas yo, Cah Ayu... iki kabeh kersane Abahmu. Insyaallah, Abah bakale ayem ning kono," Bu Nyai Khodijah berusaha menguatkan Ning Alia.
Ning Alia hanya mengangguk, mengiyakan tanpa suara.
Malam itu, di depan jenazah Abah, Gus Zaka menjabat tanganku. Di balik kaca matanya, beliau menatapku dalam, seolah menggantungkan harapan besar padaku. Laki-laki dengan kaca mata minus itu mengucapkan kalimat ijab dengan mantap.
"Qobiltu nikakhaha wa tazwijaha linafsi bil mahril madzkuri khalan..." kuucap kalimat itu dengan lantang, meski sebenarnya hatiku bergetar, pikiranku kacau.
"Bagaimana saksi, sah?"
"Sah..."
"Alhamdulillah..."
"Barakallah..."
Pak Yai Danuri, suami Bu Nyai Khodijah memanjatkan doa, mendoakan yang terbaik untuk kami. Semua orang menengadahkan tangan, mengaminkan. Setelahnya, Ning Alia menjabat tanganku, aku mengusap kepalanya sembari merapal doa-doa.
Tidak ada sambutan meriah. Tidak ada perayaan, tidak ada senyuman. Semua menangis. Bukan tangis haru, melainkan tangs kesedihan. Abah kapundut pas malam Jum'at, semoga pintu surga terbuka lebar untuk beliau.
Seusai akad, jenazah abah segera dimakamkan. Seluruh santri, keluarga, dan beberapa kerabat yang hadir turut mengantarkan abah ke tempat peristirahatan terahirnya.
***
Aku mengganti baju seusai pemakaman, lalu duduk di pendopo sambil membawa secangkir teh hangat. Kupandangi langit Kediri malam itu. Tidak ada bintang yang tampak, bahkan bulan pun enggan memunculkan wajahnya. Semesta turut berduka.
"Drrt.." Hpku bergetar. Satu panggilan masuk, dari Bulik Pah.
"Assalamualaikum, Bulik.."
"Waalaikumsalam, kepie, Le? Wis rampung kabeh?"
"Sampun, Bulik. Jenazah Pak Yai juga sudah dimakamkan."
"Owalah, sepurane ya, Le. Bulik tidak bisa datang. Paklikmu iki asam uratnya kumat, jadi tidak bisa mengantar. Bulik juga tidak tega nek meninggalkan sendiri di rumah. Zahra masih kuliah di Jogja, Ali juga sudah di pesantren. Jadi, tidak ada orang di rumah."
Tadi, sebelum maghrib aku sempat menelpon Bulik, mengabarkan pernikahan yang ujug-ujug ini, juga mengabarkan bahwa abah kapundut. Setelah bapak ibu wafat, Bulik Pah adalah satu-satunya keluarga dari ibu yang kumiliki. Rumah Bulik juga tidak terlalu jauh dari pesantren, hanya berbeda kecamatan. Aku memintanya untuk hadir, setidaknya menjadi saksi dari pihakku. Namun, beliau berhalangan.
"Nggih, Bulik, tidak apa-apa. Rozan namung ngabari mawon. Nyuwun pangstune, nggih, nyuwun doanya.." Tanpa kusadari, aku menitikan air mata.
Aku merasa terlalu kerdil bersanding dengan Ning Alia, putri Kiaiku sendiri. Dia gadis periang dengan pembawaan yang sopan, memiliki riwayat pendidikan yang bagus, sarjana Universitas Istanbul. Aku yang hanya tamatan SMA ini merasa sangat jauh di bawahnya. Bagaimana aku akan menjadi imamnya nanti?
"Ya Allah, Ngger.. Cah Bagus, sing kuat, ya. Sing tatag, sing ikhlas. Kabeh wis diatur karo kersane Gusti. Awak dewe iki bisone ming manut. Tak ewangi ndungo seko kene," ucap Bulik dengan suara parau, sesekali kudengar beliau terisak.
Aku terdiam, tak bisa berkata. Kami sama-sama terisak. Telepon masih terhubung, namun tidak ada percakapan di antara kami.
"Sampun rien nggih, Bulik. Nyuwun tambah doanya buat Rozan. Nanti tak telpon lagi. Assalamualaikum."
"Klik." Telepon kumatikan, aku tergugu di bawah langit yang sepi.
***
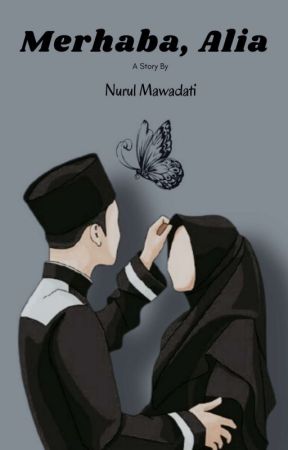
KAMU SEDANG MEMBACA
Merhaba Alia (Proses Terbit)
Tâm linhDunia Alia berbalik hampir 360 derajat, setelah kematian calon suaminya, tepat satu hari sebelum akad nikah berlangsung. Tidak cukup sampai di situ, abahnya juga menyusul wafat di hari yang sama. Sebelum wafat, Abah sempat berwasiat kepada salah sat...
