Hari sudah hampir berganti malam saat mobil Ibu memasuki halaman, sepulang dari rumah Oma. Aku bergegas menuju kamar dan membersihkan diri setelah seharian bepergian. Sedari tadi, rasanya sudah tidak tahan ingin berganti pakaian. Lebih tepatnya tidak betah memakai celana meski hanya terlihat dari lutut ke mata kaki.
Dari pengalaman hari ini, diam-diam aku jadi membenarkan lebel yang selama ini Ibu tempelkan untuk penampilanku. Ibu benar, menantunya ini memang kampungan.
Setelah selesai membersihkan diri, aku kembali mengenakan pakaian kebanggaan sebagai seorang santri. Aku harap Ibu tidak akan merasa pusing lagi saat melihat menantunya memakai sarung malam ini. Lagi pula, ini kan di rumah. Tidak ada salahnya jika memakai sarung, bukan? Masa iya setiap hari aku harus berpakaian modis.
Lama-lama, aku jadi merasa seperti maneken di butik Ibu yang harus menurut saja untuk di dandanin sesuai keinginan Ibu. Apa Ibu tak mengerti jika aku bukan boneka?
'Allohumma kamaa hassanta kholqii fahassin khuluqii.'
Aku merapalkan doa bercermin sambil memakai mukena terusan berwarna putih yang kemarin Maya ambilkan dari toko Ibu. Teringat dulu pak kyai pernah berpesan, santri putri seharusnya bercermin sebelum shalat untuk memastikan tidak ada rambut yang menyembul keluar. Karena rambut adalah aurat. Dan tidak sah sholat seorang hamba jika menampakkan auratnya walau hanya sehelai rambut.
Setelah merasa sudah rapi, aku lekas keluar kamar dan menuju masjid dekat rumah untuk shalat Magrib berjamaah. Biasanya, aku ke masjid bareng Maya. Tetapi sekarang, sendirian. Kata Mbak Rumi, Maya sedang pergi bersama Ayah entah kemana.
Setelah berjalan sekitar seratus meter, aku menginjakkan kaki kanan untuk memasuki sebuah masjid yang cukup besar. Jamaahnya juga lumayan banyak. Bersyukur, iqamah baru terdengar setelah aku sampai.
"Nduk, Ibu seperti nggak asing sama kamu." Seorang wanita paruh baya menyapaku sambil bersalaman, setelah kami selesai wirid.
Aku tahu beliau seorang ustadzah TPQ di masjid ini. Aku juga masih ingat namanya Bu Rahma.
"Saya putrinya almarhum Pak Mahmud, Bu. Tukang kebunnya Pak Ardi." Aku menjelaskan.
Wanita berwajah teduh yang duduk di hadapanku, mengernyitkan dahinya. Mungkin mencoba mengingat memori yang telah berlalu. Selarik senyum kemudian tersungging.
"Oh, iya. Ibu ingat. Terakhir ketemu waktu kamu lulus SD. Setelah itu, katanya kamu mondok di Cilacap?"
"Iya, Bu. Setelah mondok, saya jarang ke sini. Kalo liburan, seringnya pulang ke rumah Simbah. Kebetulan deket soalnya."
Setelah kepergian Ibu saat melahirkanku, Bapak memang menitipkan putri semata wayangnya ini untuk tinggal bersama simbah di Cilacap. Sedangkan, Bapak bekerja sebagai tukang kebun di perkebunan milik Ayah di Jogja.
Saat masuk SD, Bapak mengajakku untuk ikut tinggal bersamanya. Itu sebabnya, aku sudah kenal dengan keluarga Ayah sejak kecil. Tepat ketika masuk SMP, Bapak kembali mengirimku ke Cilacap untuk mondok dan sekolah.
"Ibu ikut berduka cita atas meninggalnya Bapakmu. Kamu yang sabar, ya?" Wanita itu mengusap lembut pundakku.
"Iya, Bu. Terimakasih."
"Sekarang, kamu tinggal di mana, Nduk?"
Mendengar pertanyaan Bu Rahma, aku sedikit memutar otak untuk memberikan jawaban yang tepat. Tidak mungkin aku mengaku tinggal di rumah Ayah sebagai menantunya karena Mas Danish masih belum siap mengakui gadis kucel ini sebagai istri. Dia pasti akan sangat marah. Aku juga tidak mungkin mengaku sebagai pembantu baru. Jika Ibu ataupun Ayah sampai tahu, mereka pasti akan marah.
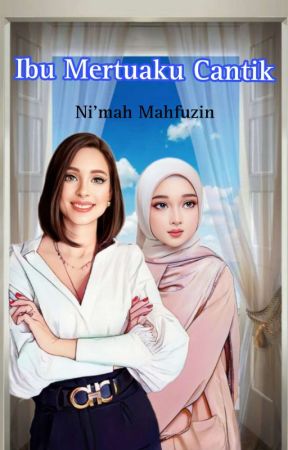
KAMU SEDANG MEMBACA
Ibu Mertuaku Cantik
RomanceAtifa Salsabila, gadis bersarung dari pesantren salaf di Cilacap yang memilih sarung sebagai pakaian santri kebanggaannya. Namun, dia harus bersedia mengubah penampilan saat terpaksa menikah dengan Danish, laki-laki temperamen yang kerap kali bersik...
