Part 2
Aku merebahkan tubuh di kasur setelah seharian berkeliling bersama Maya dan Ibu. Kaki dan punggung rasanya seperti hampir lepas dari tempatnya. Entahlah, mungkin rasanya seperti menanam padi di sawah seluas satu hektare sendirian. Bayangkan saja, berangkat dari jam delapan pagi sampai jam delapan malam baru pulang. Sudah dapat dipastikan, lelahnya tiada tara. Ditambah lagi dengan beban pikiran tentang sastra Inggris yang Ibu perintahkan.
Setelah menikah harusnya aku menjadi tenang seperti makna 'Sakinah' yang kerap orang ucapkan sebagai doa untuk pengantin baru. Kata pak kyai, sakinah itu artinya tenang atau tenteram, mawadah artinya cinta kasih, dan warahmah artinya rahmat. Tapi nyatanya, beban pikiranku justru bertambah banyak. Beban memikirkan sikap garang Ibu, sikap acuh Mas Danish, dan kuliah yang bahkan belum aku jalani.
Ah, aku lupa. Sejak ijab kabul kemarin, memang belum ada satu pun orang yang mendoakan pernikahanku supaya menjadi keluarga yang sakinah, apalagi mawaddah dan penuh rahmat.
Aku sejenak memajmkan mata. Mengingat lagi kepergian bapak yang rasanya seperti mimpi buruk.
"Mbak, mikirin apa sih? kok, melamun."
Maya merebahkan tubuhnya di sampingku yang sedang menatap langit-langit kamar. Pertanyaannya sukses menyadarkan lamunanku.
"Ibu nyuruh Mbak ambil Sastra inggris, May. Bukankah bisa kursus saja untuk belajar bahasa Inggris?" Aku membuang napas kasar.
"Bisa sih, Mbak. Tapi Mbak tahu sendiri, kan? Ibu itu gengsinya gede. Mungkin dengan Mbak ambil sastra Inggris, nanti Ibu bisa pamer ke temen-temennya kalo menantunya punya gelar."
Maya terkekeh. Aku tersenyum geli dan tak habis pikir.
Benarkah Ibu seperti yang Maya ceritakan? Bukankah Ibu tidak suka denganku? Lalu bagaimana mungkin Ibu akan menceritakan pada teman-temannya tentang gadis kampungan yang tiba-tiba jadi menantunya?
"Ehh, Mbak, bukannya waktu di pondok, ada sistem bilingual, ya? Soalnya aku punya temen-temen yang mondok. Mereka jago lhoh, bahasa Inggrisnya," ujar Maya membuyarkan lamunanku.
"Mungkin itu pondok modern, May. Kalo pondok salaf apalagi di pelosok desa kaya pondoknya Mbak kemarin, nggak ada sistem seperti itu."
Jangankan bahasa Inggris. Kadang, di pondok saja tidak semua santri bisa apalagi mahir berbahasa Arab. Karena di pondok, bahasa Jawa halus lebih diutamakan dari bahasa lain. Terutama, saat berbicara dengan Pak Kyai atau Bu Nyai. Batinku.
"Benarkah? Cerita dong, Mbak, tentang pondok. Dulu, ayah pernah nyuruh aku mondok waktu SMP. Tapi aku nggak mau. Hehe."
Maya nyengir. Dia memiringkan tubuhnya untuk menghadapku. Siap mendengarkan cerita yang dia minta.
"Dulu pas awal mondok, Mbak tiap hari nangis, May. Ada sampe semingguan kayaknya. Nggak ada temen yang kenal. Udah gitu jarang makan juga. Malu."
Aku terkekeh mengingat pengalaman pertama tinggal di pesantren.
Kebanyakan santri baru memang sering sekali menangis. Banyak hal yang bisa dijadikan alasan untuk menangis. Ada yang kangen orang tua, kangen makan enak, kangen nonton televisi, bahkan kangen bermain. Tak jarang banyak santri yang tidak bisa bertahan dan akhirnya gagal mondok.
"Bukannya kalo makan ada jatahnya, ya, Mbak?"
"Enggak, May. Kalo di pondoknya Mbak, santrinya itu masak sendiri. Ada jadwalnya bergilir. Bawa beras dari rumah. Kalo yang malu-malu, ya, harus siap sering kelaperan. Itu makanya di pondok, harus belajar ngumpul sama temen yang lain. Bersosialisasi lah, bahasa mudahnya.
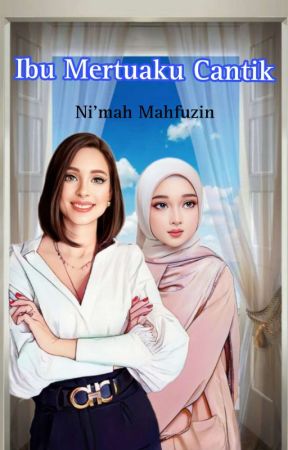
KAMU SEDANG MEMBACA
Ibu Mertuaku Cantik
RomanceAtifa Salsabila, gadis bersarung dari pesantren salaf di Cilacap yang memilih sarung sebagai pakaian santri kebanggaannya. Namun, dia harus bersedia mengubah penampilan saat terpaksa menikah dengan Danish, laki-laki temperamen yang kerap kali bersik...
