Waktu terus berlalu. Susah payah aku bertahan menguatkan hati, akhirnya hampir dua bulan pun terlewati.
Aku memandangi beberapa sarung yang tergeletak di atas kasur. Mengamati dan membolak-baliknya satu persatu. Sarung berbahan rayon dengan motif bunga-bunga yang sudah sebulan tak pernah kupakai di siang hari. Terakhir kali memakainya bepergian, hanya saat sowan ke pondok, meminta izin mukim bersama Ayah dan Maya dua minggu lalu. Selebihnya, aku memakainya saat tidur. Padahal sarung rayon ini sangat nyaman untuk dipakai dan tidak panas.
Teringat saat pertama kali tinggal di pondok, aku dan beberapa santri baru harus mengikat sarung kami dengan jilbab atau ikat pinggang karena belum bisa memakainya secara benar. Ada juga yang setiap kali memakai sarung, harus dipakaikan oleh santri senior. Sekarang, saat aku sudah mahir membuat lipatan dan melingkarkannya di pinggang dengan beberapa gulungan, Ibu justru memaksaku meninggalkannya.
Melihat sarung-sarung yang tak berdosa ini, rasanya aku ingin mengajak Ibu untuk berkunjung ke seluruh pesantren salaf. Biar Ibu tahu, betapa bidadari-bidadari cantik di penjara suci selalu memakai sarung setiap hari. Mereka bahkan terbiasa memakainya untuk pergi ke pasar atau swalayan.
Ibu hanya tidak tahu, bahkan ada beberapa pondok salaf yang melarang keras santrinya untuk memakai gamis dan mewajibkannya memakai sarung. Apa Ibu juga tidak tahu jika gadis-gadis di Madura pun banyak yang memakai sarung?
Sebelumnya, aku tidak pernah merasakan hangatnya kasih sayang seorang Ibu. Saat memiliki seorang Ibu, meskipun bukan ibu kandung, aku malah merasa menjadi orang lain. Rasanya ingin kembali ke pondok saja, biar bisa menentukan kehidupanku sendiri. Namun, jika kembali ke pondok, siapa yang akan membiayai?
Aku memang bisa menjadi santri ndalem, tapi sekarang aku sudah terikat dengan pernikahan.
Aku ingat saat meminta izin pada Mas Danish untuk pergi ke Cilacap bareng Ayah. Dia bilang, "Nggak usah minta izin! Aku nggak mau melihat wajahmu. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau."
Sejak saat itu, aku menganggapnya sebagai izin untuk setiap kegiatan yang akan kulakukan. Dengan izin itu, apa sebaiknya aku nekat saja kembali ke pondok?
"Mbak, ngapain sih, bengong sambil ngelus-ngelus sarung, gitu?"
Pertanyaan Maya seketika membuyarkan lamunanku. Dia baru saja keluar dari kamar mandi.
"Lagi kangen, May." Aku terkekeh seraya merapikan kembali sarung-sarung kesayangan dan menyimpannya di lemari.
Sungguh konyol sekali, bukan? Pakai sarung saja sampai terasa kangen.
"Mbak, boleh tanya sesuatu, nggak?" tanya Maya. Dia mengulum senyum, seperti ragu.
"Boleh. Tanya apa?"
"Kenapa sih, Mbak kalo mau wudhu pasti selalu melepas celana? Biar apa coba?"
Aku terkekeh mendengar pertanyaan Maya. Dari ekspresinya, mungkin dia merasa aneh dengan apa yang kulakukan saat akan berwudhu. Wajar saja jika dia merasa aneh. Dulu, pun aku merasa aneh dan heran saat baru mengetahui alasan di balik hal tersebut.
"Sekarang, Mbak tanya dulu. Kamu tahu kan, ada cairan yang keluar dari lubang kewanitaan selain darah?"
Aku duduk di samping Maya yang sedang mendengarkan dengan antusias di tepi ranjang. Dia mengangguk sebagai jawaban.
"Nah, cairan itu namanya madzi, wadi, mani dan keputihan," sambungku kemudian. "Mani itu nggak najis. Tapi, madzi dan wadi itu najis. Beberapa Ulama ada juga yang mengatakan kalau keputihan itu najis.
"Sementara, satu dari syarat wajib shalat itu harus suci dari hadas dan najis. Itulah sebabnya, kenapa wanita harus selalu membersihkan area sensitifnya terlebih dulu sebelum mengambil air wudhu untuk shalat."
Maya tampak mengangguk, mendengarkan penjelasanku.
"Nah, kalau bepergian, kita bisa pakai pantyliner. Biar nggak perlu membuka celana. Kan, bisa dibuang pas habis pipis." Aku menambahkan.
"Oh, gitu. Aku baru tahu." Maya menanggapi.
Sejenak, aku teringat saat mengaji kitab Inganatun Nisa. Bu Nyai pernah menjelaskan, aku akan bisa membedakan antara madzi dan mani hanya ketika sudah menikah. Sekarang, aku pun sudah menikah. Tapi, kenapa belum bisa membedakannya, ya?
Di tengah perbincangan, perut Maya terdengar berbunyi. Dia terkekeh dan mengatakan lapar.
"Mbak bisa bikin nasi goreng nggak?" tanyanya.
"Bisa. Kamu pengen nasi goreng?"
Dia mengangguk antusias. Sedetik kemudian, kami gegas menuju dapur. Kami sengaja membuatnya sendiri tanpa meminta bantuan Mbak Rumi. Maya bilang, dia ingin belajar memasak.
Maya membantuku mengupas bawang dan menyiapkan nasi serta mencuci telur. Sementara, aku yang mengulek bumbu, mengiris sosis serta bakso, lalu memasaknya. Kami hanya membuat dua porsi karena Ibu dan Ayah sedang ada acara di luar.
Setelah nasi goreng selesai dimasak, aku membaginya menjadi dua piring. Kami membawanya ke meja makan. Dari aromanaya, tercium bau yang sangat menggiurkan.
Namun, saat baru saja kami akan menikmatinya, aku dan Maya mendengar Mbak Rumi menjerit di kamarnya. Sontak, kami bergegas menghampiri. Tiba di kamarnya, ternyata dia sedang berjingkat-jingkat di atas ranjang karena melihat kecoa. Kami terkekeh melihatnya.
"Mbak Rumi bikin kaget saja. Kirain ada apa." Aku menggeleng.
"Bantuin lhoh, Mbak, tolong usirin kecoanya." Wajah Mbak Rumi terlihat memelas.
Aku hendak membantu, tapi Maya justru menarik tanganku supaya mengikutinya menuju ruang makan. Katanya, dia sudah tidak sabar menikmati nasi goreng buatan kami.
"Mbak, kok, nasi gorengnya nggak ada?!" Maya berseru, tak menemukan nasi goreng yang tadi kami letakkan di meja makan.
"Iya. Barusan kan, di sini." Aku ikut bingung.
Tiba-tiba, Maya mengambil sebuah kunci yang tergeletak di meja, lalu berlari menaiki anak tangga. Wajahnya terlihat kesal. Aku mengikutinya dari belakang, tidak tahu apa yang akan dilakukan olehnya. Sampai di depan kamar Mas Danish, dia menghentikan langkahnya, lalu mengetuk pintu kamar dengan keras.
"Mas, buka pintu!! Mas!!"
"Berisik!!" Mas Danish berteriak dari dalam.
Maya tak mau berhenti. Ia tetap saja berteriak sambil memukul pintu berkali-kali.
"Apa sih, teriak-teriak mulu? Ganggu saja!" Mas Danish akhirnya keluar.
"Mas yang ambil nasi goreng di meja makan, kan?"
"Nggak!"
"Ngaku!"
"Apa buktinya kalo Mas yang ambil? Jangan nuduh sembarangan!"
Aku mencoba menarik tangan Maya supaya mengudahi pertengkaran. Kami bisa membuatnya lagi. Namun, dia mengbaikan.
"Terus ngapain kunci motor Mas ada di meja? Tadinya nggak ada." Maya menunjukkan sebuah kunci di tangannya.
"Mana Mas tahu." Mas Danish mengedikkan bahu. "Kabur kali kebawa angin."
"Ih. Aku sama Mbak Atifa udah capek-capek masak, seenaknya ajah Mas ambil."
"Halah. Nasi goreng nggak enak juga."
"Nah kan, ngaku juga akhirnya."
Aku yang berdiri di dekat Maya, hanya memperhatikan perdebatannya dengan Mas Danish sambil menahan tawa. Maya terlihat begitu geram saat mendapati kakaknya hanya terkekeh.
Maya mendorong tubuh Mas Danish ke atas ranjang, lalu memukulinya dengan bantal berkali-kali. Lucu sekali. Laki-laki kasar itu, selain bisa membentak, ternyata juga bisa mengambil milik orang lain tanpa izin. Aku tahu karena ada dua piring kotor yang tertumpuk rapi di atas nakas.
Seharusnya, aku ikut marah. Tapi, entah kenapa aku justru senang mendapati Mas Danish menghabiskan nasi goreng itu. Rasanya ... entahlah. Sulit untuk mendeskripsikannya dengan kata-kata.
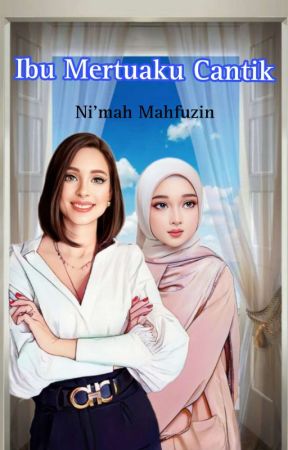
KAMU SEDANG MEMBACA
Ibu Mertuaku Cantik
RomantiekAtifa Salsabila, gadis bersarung dari pesantren salaf di Cilacap yang memilih sarung sebagai pakaian santri kebanggaannya. Namun, dia harus bersedia mengubah penampilan saat terpaksa menikah dengan Danish, laki-laki temperamen yang kerap kali bersik...
