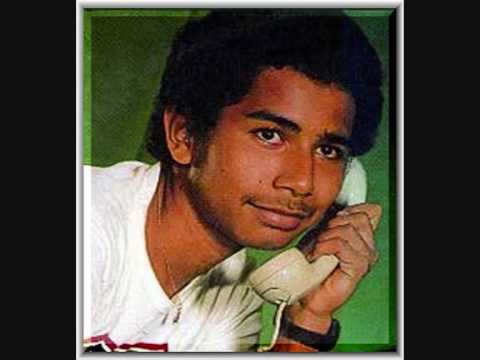"It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages."
(Friedrich Nietzsche)
Selama hidup Ina tidak pernah merasa segentar itu. Dia selalu memiliki Navid dan Zora yang akan membela dan berdiri di depan Ina. Apa pun kesalahannya, sebesar apa pun dosanya, gadis itu selalu memiliki sekutu. Namun kini persoalannya jauh berbeda. Dia harus menghadapi semuanya sendiri jika tidak ingin membiarkan masalah kian melebar.
Kepala Ina terasa berdenyut kencang. Jika dia mengadu pada Navid dan berharap mendapat pembelaan, Ina tak yakin harapannya akan tercapai. Alasannya simpel saja. Ayah mereka masih belum melupakan insiden yang melibatkan si kembar dengan Sonya, bahkan sampai berencana untuk menjodohkan Ina dan Zora. Entah serius atau tidak.
Jika sekarang Navid mendengar ulah terbaru Ina, sudah pasti ayahnya akan murka lagi. Apalagi jika Navid tahu alasan Ina bisa menyetir saat seharusnya sedang makan malam Martin. Ina tak berani membayangkan seperti apa kemarahan ayahnya. Jadi, Ina harus bisa mengatasi masalah ini sendiri.
"Ina, saya tahu kalau kamu pasti kaget mendengar permintaan kami. Tapi, semuanya ada alasannya," ujar Claire dengan suara lembut yang membujuk. Ina pun kembali pada kekinian, menyadari situasi pelik yang sedang dihadapinya.
Ina mendapat satu kejutan besar lagi dalam kurun waktu beberapa detik kemudian. Gadis itu tadinya hendak merespons kata-kata Claire tap batal karena Binsar telanjur membuka mulut. Efek dari kata-kata yang diucapkan lelaki itu adalah gelombang rasa takut yang mencuri napas Ina. Betapa tidak? Binsar dengan lancar mengulas alasan kenapa mengajukan permintaan aneh itu kepada Ina.
"Saya kenal baik dengan ayahmu, Navid Kusuma. Saya juga mengenal Tobias Mananta, juga rencana perjodohan kamu dan anaknya. Meski saya belum yakin sejauh mana rencana itu akan diwujudkan. Selama beberapa hari ini, saya mencari tahu tentang kamu, Inanna Grace." Binsar menatap Ina dengan serius.
Kalimat itu membuat Ina menelan ludah dengan susah payah. Tengkuknya serta merta terasa membeku. Tenggorokan Ina mendadak nyeri, seakan ditumbuhi duri. Perasaannya kian memburuk seketika. Alarm bahaya berdentang di kepalanya, memberi peringatan bahwa dia sudah memasuki situasi genting.
"Papa saya tidak benar-benar berniat menjodohkan saya dan Martin, Pak," balas Ina dengan suara lirih. "Papa cuma sedikit menakut-nakuti saya," imbuhnya. Setelah menyadari bahwa dia sudah memberi informasi terlalu banyak, Ina buru-buru mengatupkan bibir. Untuk apa dia menyinggung soal "menakut-nakuti" itu?
"Anggaplah itu benar. Bukan berarti...." Binsar mengehentikan kata-katanya sesaat. Alisnya terangkat. "Ah, sebenarnya ini tidak benar-benar ada hubungannya dengan rencana perjodohan itu. Saya cuma ingin memberi sedikit harapan untuk Alistair." Binsar menarik napas panjang. Lelaki itu malah menatap istrinya, entah meminta dukungan atau persetujuan. Ina kebingungan dengan apa yang dilihatnya.
"Harapan? Maksudnya apa, Pak? Apa kecelakaan kemarin itu sudah memberi efek buruk? Bukankah Alistair sudah diizinkan pulang setelah dirawat sehari? Apa ada masalah baru? Kenapa saya tidak diberi tahu?" tanya Ina bertubi-tubi. "Saya tidak akan lepas tanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Saya sudah menyanggupi untuk mengganti semua biaya perawatan Alistair," kata Ina dengan gagah.
Dia sedang berupaya menenangkan hati orang tua yang tampaknya sedang gundah ini. Sesaat kemudian, Ina mengingatkan dirinya agar mengerem kata-katanya. Ini salah satu kelemahan serius gadis itu. Ada gen pahlawan kesiangan yang mengalir di dalam tubuhnya. Ina cukup sering mengambil peran sebagai si pemecah masalah dengan terburu-buru tanpa memikirkan efeknya. Dia memang sok jago.
Binsar menggeleng pelan. "Ini bukan soal biaya, Ina. Tanpa bermaksud menghina, kami masih bisa mengatasi masalah uang. Kami meminta bantuanmu untuk masalah lain, yaitu soal nyawa."
Ina nyaris menjerit ketakutan kalau saja dia tidak buru-buru menggigit lidah. Dia bisa merasakan darah di mulutnya. Namun Ina melupakan rasa nyeri yang mencubit itu dan sudah pasti akan membuat dirinya menderita sariawan. Konsentrasinya diruahkan untuk hal lain yang jauh lebih merusuhkan hatinya.
"Nya ... wa?" Ina tergagap.
Claire yang merespons, dengan suara tenang. "Keluarga saya berasal dari Australia. Kami hanya punya dua orang anak, Alistair dan Josette. Kedua anak saya berkuliah di Australia. Saat ini, Jo sudah menikah dan saat ini sedang hamil. Dia menikah dengan pria setempat dan menetap di Australia. Al sendiri baru beberapa tahun tinggal di Jakarta.
"Sebelumnya, dia juga bermukim di sana. Selama ini, urusan pekerjaan ditangani oleh suami saya. Tapi saat suami saya mau pensiun, maka Al dipanggil pulang. Awalnya dia tidak mau, tapi kami harus sedikit memaksa. Jo sendiri tidak mungkin kembali ke sini karena dia punya keluarga di sana. Jadi, karena Al masih lajang, mau tak mau dia yang harus berkorban."
Ina menyabarkan diri, mendengarkan dengan patuh kalimat panjang yang sepertinya baru merupakan pembuka itu. Padahal, dia sungguh tak nyaman di tempat duduknya. Seakan kursi yang ditempatinya sudah ditumbuhi duri dengan misterius.
"Al itu harapan kami, satu-satunya anak lelaki di keluarga Damanik. Kalau dia tak mau pulang, akan sangat merugikan bagi keluarga kami. Saya dan papanya harus membujuk Al mati-matian supaya mau kembali ke Indonesia. Saya bersyukur karena dia pun akhirnya setuju untuk ikut mengurus hotel. Ada banyak anggota keluarga suami saya yang siap membantunya. Oh ya, kamu pernah mendengar nama PT Bintang Beralih, Ina?"
Respons Ina adalah gelengan kepala. Dia sedang tidak ingin menggali memori. Otaknya tidak mampu bekerja, kram, dan beku. Dia hanya termangu saat Claire menjelaskan secara singkat seputar bidang usaha yang dijamah oleh Bintang Beralih. Ada hotel, supermarket, toko buku, hingga restoran.
"Bintang Beralih itu usaha milik keluarga besar Damanik. Al membantu mengurus hotel, bersama dua orang paman dan beberapa sepupu." Claire mendadak menoleh untuk menatap suaminya. Senyum perempuan itu mengembang cantik. Namun tetap tak mampu menyembunyikan kemurungan yang jelas terlihat di ekspresinya. "Ah, Ina mungkin bosan mendengar cerita kita," Claire bicara pada Binsar.
"Lalu, apa hubungannya dengan ... nyawa ... tadi?" desak Ina dengan halus. Dia tak sanggup jika diminta terus menunggu. Gadis itu berusaha keras menyembunyikan ketidaksabaran sekaligus rasa penasarannya. Namun sepertinya tak sepenuhnya berhasil.
"Suami saya sudah tua, memang sudah seharusnya pensiun. Dia sudah bekerja keras puluhan tahun membesarkan Bintang Beralih," tangan Claire memerangkap punggung tangan suaminya di atas meja. "Tapi tampaknya masalah pekerjaan ini cuma masalah kecil. Kami harus menyiapkan mental untuk menghadapi persoalan yang lebih menakutkan. Al...." Claire terdiam. Perempuan itu tertunduk. "Al...."
Binsar yang kemudian bicara, dengan nada datar. "Alistair menderita penyakit serius. Dokter sudah...." Binsar memeluk bahu istrinya. "Maaf Ina, saya kesulitan tiap kali membicarakan soal ini. Yang jelas, Alistair tidak akan hidup selamanya. Karena itu, kami ingin membahagiakannya. Kami ingin dia menikah. Anggaplah sebagai hadiah terakhir yang bisa kami berikan sebagai orang tuanya."
Ina melongo. Benar-benar tidak bisa melihat hubungan antara penyakit Alistair dengan dirinya.
"Lalu, kenapa Bapak ingin saya menikah dengan dia? Saya rasa, Alistair pasti punya pacar. Kalaupun tidak, dia pasti takkan setuju menikah dengan cara dijodohkan seperti ini. Hmmm ... sudah bukan zamannya menikah dengan cara begitu, kan? Saya sendiri belum tertarik untuk berumah tangga. Mungkin, saya baru akan berkeluarga enam atau tujuh tahun lagi."
Pasangan itu saling tatap untuk sesaat, tampak kaget dengan kata-kata Ina.
"Enam tahun itu masih lama, Ina. Kami cemas tidak akan ada waktu yang cukup. Al cocok denganmu, percayalah. Dan dia pasti akan setuju. Kami sudah melakukan semacam ... hmmm ... penelitian kecil-kecilan. Kamu mungkin tidak tahu, tapi saya dan Navid adalah teman lama. Cuma memang sekitar empat atau lima tahun belakangan, kami sudah jarang bertemu. Masing-masing memiliki kesibukan yang tak bisa ditinggalkan." Binsar berdeham. Lelaki itu kembali bertukar tatapan dengan sang istri.
Claire yang bersuara kemudian. "Saat ini, kami cuma menginginkan bantuanmu. Kami ingin Alistair merasakan hidup yang bahagia. Tolong ya, Na. Karena ... kanker otaknya tidak mungkin menunggu."
Lagu : Jerat (Harvey Malaiholo)

KAMU SEDANG MEMBACA
Fix You
ChickLitIni kisah tentang pernikahan tanpa cinta. Ah, pasti kisah tentang salah satu calon mempelai yang kabur dan terpaksa digantikan oleh saudaranya? Sayangnya, bukan. Ini pernikahan yang melibatkan kecelakaan, kanker otak, gadis nakal yang sering kehil...