Oktober di Berlin, dingin serta sedikit berangin. Cuaca autumn dari bulan September-November di negara dengan empat musim ini, sebenarnya tergolong yang terbaik menurutku, kalau dibandingkan dengan tiga musim lainnya (spring, summer dan winter).
Tapi tetap saja aku masih susah menikmatinya, padahal dulu aku juga sempat tinggal di negara dengan empat musim, tepatnya di San Diego, United States selama dua tahun untuk lanjut studi master. Tapi, sejujurnya itu tidak bisa dijadikan perbandingan.
San Diego jelas lebih hangat dari Berlin, seingatku dulu rata-rata suhunya sekitar 68 derajat fahrenheit atau sekitar 20an derajat celcius. Sejuk seperti di ruangan ber-AC, sangat berbeda dengan saat ini.
Aku memeriksa informasi weather di ponselku, tertera angka 9 derajat celcius. Makin kurapatkan jaket tebal yang sudah kupakai sejak di Berlin Brandenburg Airport. Mestinya tadi mesen taksi aja. Aku menyesali keputusanku beberapa waktu lalu untuk ke airbnb-tempat istriku dan manajernya menginap, di daerah Bernburger straße dengan U-Bahn (Untergrundbahn/Subway/Kereta bawah tanah).
Tadinya aku ingin berlagak sok sehat setelah 13 jam lebih duduk di penerbangan panjang, dengan memaksa kakiku bergerak alih-alih terjebak lagi di kursi mobil. Padahal kalau memesan taksi aku bisa hemat waktu setengah jam lebih cepat untuk sampai di airbnb. Nggak papa, 100euro daripada buat bayar taksi mending buat beli 10 döner-sandwich dari roti pita hangat isi daging, sayur juga aneka saus yang dipopulerkan imigran Turki di Berlin, buat Titah dan seluruh timnya.
Aku jauh-jauh ke Berlin memang untuk menyusul istriku yang sedang ada job manggung di sini. Kata Ocha-manajer Titah yang menggantikan posisiku sejak aku kuliah di US, Titah mengisi acara tahunan anak-anak PPI Berlin. Penampilan itu sudah selesai dua hari lalu, tapi istriku dan timnya tentu saja memperpanjang hari berada di Jerman demi liburan.
Aku begitu percaya diri awalnya, tidak akan merasa kangen ketika ditinggal kerja beberapa minggu ke luar negeri, toh aku juga sibuk belakangan ini. Menggarap film panjang animasi pertamaku yang akan ditayangkan di bioskop paling cepat lima tahun lagi.
Tapi nyatanya aku butuh menemui istriku, bukan cuma sekedar untuk membayar rasa kangen, melainkan mengusahakan sebuah rekonsiliasi. Beberapa waktu sebelum Titah ke Jerman, kami sempat berdebat panjang soal kontrasepsi.
Hampir setahun menikah, kami memang masih sama-sama teguh dengan rencana menunda kehamilan. Titah belum siap jadi ibu, dan belum bisa mengurangi jadwal manggungnya secara tiba-tiba. Akupun sama, belum siap dengan tanggung jawab besar sebagai ayah, di saat sedang sibuk-sibuknya merintis studio animasiku sendiri.
Sejauh ini kami sepakat memakai kontrasepsi alami dengan cara menghindari berhubungan intim saat Titah mengalami masa ovulasi. Selain itu, aku juga selalu pakai kondom selama bercinta. Semuanya baik-baik saja, sampai suatu malam di akhir percintaan kami, bahkan ketika itu kami masih telanjang berpelukan.
Titah seenaknya merengek kesal, merusak suasana romantis yang sedang membuaiku. "Jujur ya, aku ngerasa nggak terlalu happy ngelakuinnya. Aku capek harus selalu hati-hati."
Dia bergerak melepaskan rangkulanku, tapi kutahan sebentar. "Ya kalau kita nggak hati-hati, terus ntar kebobolan, kamu hamil gimana? Emang kamu udah siap ninggalin panggung-panggung kamu?" Aku bersumpah saat mengatakan itu, tidak ada tendensi untuk menyudutkan istriku. Tapi Titah menangkapnya berbeda.
"Ya, kamu juga nggak siap kan sekarang, kalau harus mecah fokus ke anak, padahal projek-projek kamu baru mulai jalan dan keuangan bisnis kamu belum terlalu stabil." Titah membalasku dengan begitu sengit.
"Yaudah mau gimana lagi. Ini pilihan kita bersama."
"Aku nggak nyaman selalu was-was tiap kita making love. Aku mau ganti kontrasepsi, aku mau pasang KB implan."
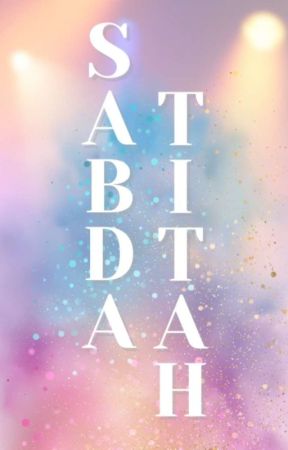
KAMU SEDANG MEMBACA
SABDA TITAH
ChickLit"PENGECUT KAMU SABDA. MESTINYA KALAU KAMU SUKA AKU ITU BILANG. BUKANNYA NYIMPEN SENDIRIAN, TERUS SEKARANG NINGGALIN AKU SEENAKNYA." -Titah Cinta, penyanyi 23 tahun yang ditinggal manajernya pas lagi sayang-sayangnya. "Ta, ta. Semoga kamu makin dewa...
