Pohon lapuk yang tak kunjung ditebang di taman belakang sekolah adalah tempat ternyaman. Di sini pula aku untuk sekarang, berteduh di bawahnya. Henti hanya omong kosong untuk tangan kanan yang lihai menulis dan menghapus kelompok kata.
Seperti biasa, lalat-lalat mengajakku bercengkrama dengan dengungan mereka tiap kali aku ke sini. Kemudian, aku hanya memberi cengir untuk komunikasi balasan.
Aku sudah duduk di sini sejak jam pelajaran yang terbengkalai akibat para guru tengah rapat untuk persiapan penilaian tengah semester genap. Aku tahu, apa yang kulakukan sesungguhnya sebuah pelanggaran. Bahkan terus kuulangi berkali-kali. Namun, bila aku terus saja berdiam di kelas, aku akan dihadapkan dengan mereka yang ganggu ketenangan. Aku tak mau.
Belum ada poin untukku selama aku melanggar, untungnya.
"Kalo begini, jadinya alay banget, ah!" cibirku pada puisi yang tak juga siap dari seminggu yang lalu.
"Duh! Mana masih satu bait lagi. Ayo, dong! Mikir kek Aska!" Gebukan di kepala terasa olehku sendiri, saking frustasinya.
Tiba-tiba, aku terperangah dengan pelafalan namaku yang tersebut di belah bibir sendiri. Nama itu. Layaknya stop-kontak yang menyalakan lampu, pikiran pun turut menyala dengan satu nama, yang sayangnya tak kulihat helai rambutnya sekalipun dari beberapa hari terakhir.
Marine. Marine. Marine.
Berisik.
Spontanitas yang tercipta yakni pukulan yang kuarah pada kepala, lagi. Benci kala otak justru mendesis dengan frekuensi begitu besar mengucapkan nama itu. Efeknya besar di sekujur badan. Terbang, tenggelam, lalu terbang lagi, tenggelam lagi. Diombang-ambing dengan perasaan manusia yang lumrah terjadi manakala tak berjumpa untuk beberapa waktu; rindu.
Aku melemaskan tubuh, bersandar pada pohon dengan sebelumnya memerhatikan cermat. Siapa tahu masih ada jejeran semut memanjat di pohon yang buat gatal. Setelah memastikan tak ada, aku segera menempelkan punggung dan kepala.
Pandangan mengacu pada teman-temanku di sini; para lalat. Jikalau menelisik mendalam, jadi lalat itu tak sepenuhnya menjengkelkan. Mereka hanya perlu bertahan hidup yang sangat jauh lebih singkat dibandingkan lalat jadi-jadian sepertiku. Tidak perlu punya perasaan lantaran tak dibutuhkan. Tidak perlu merindukan seseorang yang tak merindu balik.
Lagipula, untuk apa kalau Kak Marine ditimpa rindu dengan seorang perempuan cupu dan terasingkan ini?
Lembaran putih di buku masih mengangkang. Menampilkan tulisan seminggu lalu yang pada akhirnya belum ditambahi apa-apa. Sia-sia. Aku memutar mata malas.
Lebih baik aku tidur saja sampai istirahat jam pertama berakhir.
"Males banget, masa iya kelas seni malah ngebersihin taman belakang sekolah?"
"Iya, ih! Padahal tempat kumuh gini dijadiin tempat kelas seni! Sinting!"
"Semuanya gegara si Marine, noh! Malah ngide!"
"Namanya juga berkebun. Ya, pasti gak jauh dari tanaman. Lagian, kelas seni berkebun tuh sebenernya ya jadi babu ngurusin tanaman."
"Tapi gak di sini juga!"
"Di sini juga banyak tanaman sebenernya. Tapi terbengkalai. Udah deh, para babu! Mending diem, ya!"
"Sadar diri, anjir! Lo juga babu!"
"Siap salah, rekan babi—eh, babu!"
"Udah-udah, malah pada berisik!"
Baru saja memejamkan mata semenit, kudengar kicauan beberapa orang yang terdengar begitu bergegas di sini. Oh, dan suaranya, suara Kak Marine di antara perbincangan sana. Sial, bergegas pula aku membuka mata.
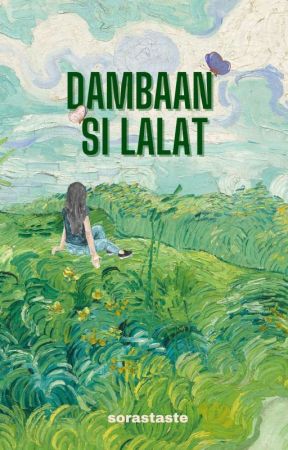
KAMU SEDANG MEMBACA
Dambaan Si Lalat [Bbangsaz]
FanfictionTak pernah absen Hanita mengecap diri sendiri sebagai lalat. Seekor serangga yang tak akan bisa dipandang keindahannya, orang-orang selalu mencerca karena dianggap pengacau dan kotor. Dia terlalu buruk untuk masih berpijak di buana luas yang membent...
![Dambaan Si Lalat [Bbangsaz]](https://img.wattpad.com/cover/345971160-64-k532729.jpg)