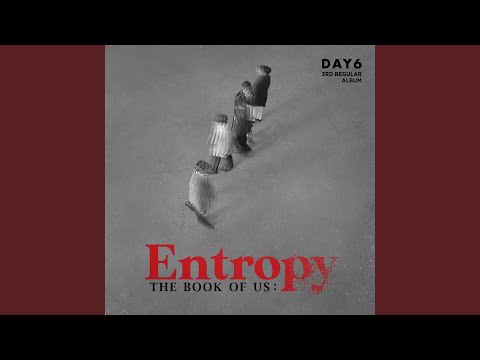"Because I really love you
Maybe that's why it hurts this much."
DAY6; Like A Flowing Wind.
***
Sepasang mata sembap.
Adalah hal yang kali pertama saya temukan saat mematut diri di depan cermin kamar.
Saya lupa berapa lama waktu yang saya habiskan untuk menangis kemarin, saya lupa kapan saya berhenti, saya lupa kapan saya tertidur, sampai saya lupa ajakan makan malam bersama dari Mama.
Padahal harapan saya cuma satu; seandainya bisa, saya ingin sekali lupa akan alasan apa yang membuat saya jadi porak-poranda seperti ini.
Tarikan tipis serta helaan napas selanjutnya saya embuskan perlahan, mencari sugesti diri untuk tetap bertahan dan berpikir positif sebelum langkah saya kembali menyambangi realita-realita lainnya.
Segalanya akan baik-baik saja, Rianka,
Semoga.
***
Satu hal yang paling tidak saya sukai selama dua puluh empat tahun hidup adalah membawa payung ke mana pun saya pergi. Tetapi karena mengingat motor saya masih teronggok tidak berdaya di garasi rumah, dilengkapi hujan yang sedang senang-senangnya turun di sembarang waktu, mau tidak mau saya harus mengalahkan rasa ketidaksukaan saya yang satu itu.
Jarak sembilan meter dari tempat awal di mana saya membuka payung untuk mencapai selasar kantor seperti terasa lebih berat, seperti terasa lebih panjang, seperti terasa mereka memanjangkan diri hingga tiga kali lipat.
Entahlah, mungkin hanya karena saya enggan. Atau akhirnya karena saya menyadari bahwa untuk pertama kali, saya benci menjadi seorang yang profesional dan terlalu patuh pada peraturan sampai mengabaikan bagaimana diri tengah tidak siap menghadapi bias apa pun.
Menelisik arloji pada pergelangan tangan kanan, saya baru menduduki bangku milik sendiri pada pukul tujuh lima belas. Beberapa kubikel di kanan dan kiri saya masih terlihat sepi, dan beberapa dari mereka yang sudah datang masih mengobrol santai.
Saya menoleh, bangku di belakang sana belum terisi.
Andai Bian ada saat ini, mungkin level kemurungan saya dapat tertutupi oleh candaan-candaan keringnya.
Tetapi kembali saya berpikir, untuk apa sebenarnya saya murung? Saya bahkan belum mencoba membuktikan apa pun.
"Rianka?"
"Ya?" Saya menyembulkan kepala dari balik kubik, tertuju pada teman seruangan saya.
"Dipanggil Pak Alan tuh di ruangannya."
"Oh, iya, bentar."
Saya menghela napas panjang, menyimpan jaket pada sandaran bangku lantas segera beranjak menuju ruang kerja milik manajer saya.
Tidak ada satupun gambaran yang bisa saya terka mengenai kenapa saya bisa dipanggil sepagi ini oleh seorang kepala divisi. Saya jadi mengingat-ingat hari kemarin, apakah karena saya terburu-buru pulang untuk menolak realita menyebabkan pekerjaan saya harus tertinggal?
"Ganggu, ya? Udah mulai kerja kamu?"
Saya menggeleng pelan. "Belum, Pak. Bagi tugas juga belum."
"Bagus deh."
"Ada apa, Pak?"
Pak Alan tersenyum simpul sambil meraih sebuah amplop putih dari dalam laci mejanya.
Kemudian begitu saja diserahkan ke hadapan saya. "Buat kamu. Titipan dari Bian."
Saya tertegun.
"Dia ikut pertukaran pegawai ke Jepang, dan kemarin hari terakhir dia kerja bareng sama kita. Kemarin juga farewell dia nyariin kamu, tapi karena kamu udah pulang duluan jadi ya ... kayaknya dia cuma mau kasih ini, dititipin sama saya." Pak Alan tertawa ringan. "Aneh nggak sih, tinggal kabarin lewat chat aja padahal."
Iya, aneh.
Dunia terkadang memang seaneh itu. Dan Bian ambil andil di dalamnya.
Di saat saya butuh teman untuk mencoba lupa, dia tidak ada. Tidak ada lagi dia yang tertawa mendengar jawaban-jawaban spontan saya, tidak ada lagi dia yang mengajak saya untuk menjadi seorang pegawai bandel, atau tidak ada lagi kata-katanya yang seringkali memancing segala kuriositas saya.
Menyisakan saya seorang diri di dalam kubikel ini. Bangku kosong di belakang sana seolah menatap saya iba, seolah saya bisa runtuh kapanpun itu ketika bahu saya tidak mampu lagi menghadap layar laptop dengan tegap.
Terlebih, sewaktu suara langkah dari kaki berbalut hak tinggi dari ujung koridor terdengar mendekat dan semakin mendekat.
Bahu saya seperti terguncang, setelah mengetahui siapa yang mendatangi saya dengan tegas bersama dua map hijau di tangan, dan tatapan tak bersahabat yang mematikan nyali saya dalam waktu kurang dari satu sekon.
"Ini apa, Qir?" Tanya saya takut-takut, sebab ia tidak kunjung menjelaskan.
"Tanda tangan laporan bulanan."
"Oh, ya udah nanti saya isi. Terus saya aja yang bawa."
Beberapa detik setelah saya menerima map tersebut, Qiara tidak menjawab namun masih berdiri di sana. Di tempat yang sama.
"Rianka, aku nggak tahu apa yang ada di pikiran kamu."
Saya batal mendongak menemui keras ekspresinya.
"Tapi Malik itu punya Jia, mereka pacaran, kalau kamu nggak tahu." Qiara menjeda, menghela napas kesal. "Aku ngomong begini karena lama-lama aku lihat, Malik jauh lebih dekat sama kamu daripada sama Jia sendiri. Aku temen deketnya Jia, aku tahu gimana perasaannya Jia."
Saya terdiam, tanpa sadar sudah menunduk.
"Hati-hati kamu, Rianka, dan tolong hargai Malik sama Jia, terlebih Jia, karena kita sama-sama perempuan." Decak tak sabar terdengar sebelum Qiara hendak berbalik. "Aku harap kamu ngerti."
Hentakan langkah kasar itu langsung menjauh, seakan menolak saya mentah-mentah untuk membuka mulut sedikit dan memberi penjelasan barang satu ujaran.
Ternyata benar, semua intuisi saya tempo hari benar, tidak ada yang meleset.
Terlintas lagi di otak saya bagaimana retorik saya terasa membeku sesaat setelah suara tawa bahagia Malik terdengar menggelitik rungu saya, bersama seorang perempuan yang tidak saya ketahui siapa dan tidak ingin saya ketahui dengan lancang sebab saya bisa dengan jelas melihat perempuan di samping Malik waktu itu merangkul si lelaki erat sekali.
Kembali saya berpikir, saya kini mengerti mengapa saya tenggelam dalam kemurungan. Itu mungkin, hanya karena saya tidak perlu repot-repot mencoba membuktikan soal apa pun.
Saya memutar bangku sedikit, lagi-lagi menemukan presensi bangku kosong di sana. Menyadarkan bahwa saya benar-benar akan melewati ini seorang diri, tanpa siapa pun yang akan membela saya, tanpa ada yang mau percaya pada segala pembelaan terlambat milik saya.
Detik demi detik terlewati, di saat riuh rendah di sekitar saya semakin ramai, justru saya semakin menunduk dalam-dalam. Memutus pandangan basah memburam saya dari sudut penghakiman manapun, hanya tersisa sedikit celah untuk memandangi map hijau di atas meja yang bahkan belum saya sentuh sama sekali.
Saya tidak bisa mengelak sekuat apa pun saya mencoba, jatuhan air mata teratur saya jauh lebih banyak jumlahnya. Saya hanya berharap, dunia luar menjadi tuna rungu sesaat untuk isak saya yang tidak sepatutnya mereka dengar, sekaligus memutar satu pertanyaan sama berulang yang sangat saya butuhkan jawabannya sebelum tangis saya semakin meledak,
Jadi, semua ini, salah saya?
***
A/N :
Mewek ngga kalian aaaaaaaaa aku nulis sendiri mewek sendiri ;;_;; *menyodorkan tissue*

KAMU SEDANG MEMBACA
Why We Here
FanficPernahkah kamu bertanya, mengapa kita ada di sini? (Was) #1 - hajoon #1 - the rose [ Why We Here ; DAY6's ] ©2020, Nyctoscphile (200320ㅡ210828) All Rights Reserved.